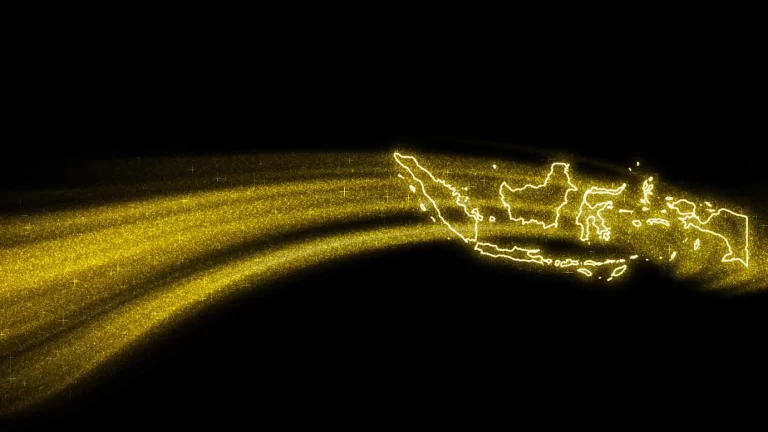
Semua tentang
Kearifan Lokal Indonesia

Suku Baduy Asal Muasal & Kepercayaannya
Suku Baduy merupakan sekelompok masyarakat adat yang hidup di Kawasan hutan pedalaman di Kaki Gunung Kendeng Banten, Jawa Barat. Jumlah penduduk suku Baduy sekitar 26.000 orang, termasuk kelompok masyarakat yang sangat tertutup dari dunia luar. Masyarakat suku Baduy masih termasuk ke dalam sub-suku Sunda, yang belum terkontaminasi modernisasi dan masih memegang tradisi serta adat khas yang hampir seluruhnya tertutup dari dunia luar. Agama yang dianut oleh masyarakat suku Badui adalah Sunda Wiwitan, yang merupakan perpaduan antara Islam dan Hindu. Apa Itu Baduy? Nama “Baduy” adalah sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut, namun menurut cerita hal ini berawal dari sebutan para ilmuwan asing yang sepertinya menyamakan mereka dengan sekelompok etnik Arab Badawi yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah (nomaden) jazirah Arab. Alasan lainnya adalah terdapat Sungai Badui dan Gunung Badui di bagian utara dari wilayah yang mereka diami. Suku Baduy sendiri lebih suka disebut sebagai urang Kanekes atau “orang Kanekes” sesuai dengan nama wilayah mereka, atau sebutan lain yang sesuai dengan nama kampung mereka seperti Urang Cibeo. Asal Usul Suku Baduy Ada beberapa versi cerita tentang asal – usul suku Baduy. Yang pertama menurut kepercayaan mereka, orang Baduy merupakan keturunan dari Batara Cikal. Yaitu salah satu dari tujuh dewa yang diutus ke bumi. Ada juga yang sering menghubungkan asl usul tersebut dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama. Jauh sebelum berdirinya Kesultanan Banten, kawasan barat pulau Jawa ini adalah bagian penting dari Kerajaan Sunda. Banten adalah salah satu pelabuhan dagang yang cukup besar pada waktu itu. Sungai Ciujung yang berada di wilayah Banten dapat dilayari berbagai jenis perahu, serta banyak digunakan untuk pengangkutan hasil palawija dari wilayah pedalaman. Oleh karena itu penguasa wilayah tersebut pada saat itu yaitu Pangeran Pucuk Umun, menganggap bahwa kelestarian sungai perlu dipertahankan. Maka dari itu diutuslah pasukan tentara kerajaan yang sangat terlatih untuk menjaga dan mengelola kawasan hutan. Kawasan hutan lebat dan berbukit itu berada di wilayah Gunung Kendeng tersebut. Keberadaan pasukan dengan tugasnya yang khusus tersebut tampaknya menjadi asal muasal Masyarakat Kanekes yang sampai sekarang masih menempati wilayah hulu Sungai Ciujung di Gunung Kendeng tersebut. Perbedaan Versi Sejarah Suku Baduy Versi lain menyebutkan bahwa masyarakat Kanekes dikaitkan dengan Kerajaan Sunda yang sebelum keruntuhannya pada abad ke-16 berpusat di Pakuan Pajajaran (Kota Bogor sekarang). Perbedaan pendapat tersebut mengindikasikan bahwa pada masa lalu, identitas asli dan kesejarahan orang Baduy sengaja ditutup, dengan tujuan untuk melindungi komunitas Kanekes sendiri dari serangan musuh-musuh Pajajaran. Namun Menurut Danasasmita dan Djatisunda (1986: 4-5) orang Badui adalah penduduk asli daerah tersebut yang dijadikan mandala’ (kawasan suci) secara resmi oleh raja, oleh karenanya penduduknya berkewajiban memelihara kabuyutan (Nenek Moyang) Jati Sunda atau ‘Sunda Asli’ atau Sunda Wiwitan. Maka dari itulah agama asli mereka pun diberi nama Sunda Wiwitan. Baca Juga : Misteri Gunung Padang Agama dan Kepercayaan Kepercayaan orang Kanekes / Baduy disebut dengan ajaran Sunda Wiwitan. Merupakan ajaran leluhur turun temurun yang berlandasakan pada penghormatan kepada karuhun atau arwah leluhur serta pemujaan kepada roh kekuatan alam (animisme). Walaupun bagian besar aspek ajaran ini adalah original tradisi turun-temurun, namun pada perkembangannya ajaran leluhur ini juga sedikit dipengaruhi oleh beberapa aspek ajaran Hindu, Buddha, dan dari ajaran Islam. Sangat Menghormati Alam Bentuk penghormatan kepada roh kekuatan alam ini diimplementasikan lewat sikap menjaga dan melestarikan alam. Yaitu dengan merawat alam sekitar (gunung, bukit, lembah, hutan, kebun, mata air, sungai, dan segala ekosistem di dalamnya). Serta memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada alam. Hal ini ditunjukan dengan cara merawat dan menjaga hutan larangan sebagai bagian dalam upaya menjaga keseimbangan alam semesta. Pikukuh Suku Baduy Inti dari kepercayaan tersebut ditunjukkan dengan adanya pikukuh atau ketentuan adat mutlak. Ketentuan ini dianut dalam kehidupan sehari-hari orang Kanekes (Garna, 1993). Isi yang sangat penting dari ‘pikukuh’ (kepatuhan) Kanekes tersebut adalah konsep “tanpa perubahan apa pun”, atau perubahan sesedikit mungkin. Maka dari itulah hingga saat ini seperti tidak ada yang berubah dengan kondisi dan keberadaan masyarakat suku Baduy. Cek Video Perjalanan ke Cikeusik Di Channel Kami : Perjalanan Seru ke Cikeusik Baduy

Sekilas Tentang Tanah Ulayat – Tanah Masyarakat Adat Indonesia
Tanah ulayat, dalam konteks Indonesia, bukanlah sekadar lahan yang dimiliki secara individual atau diatur oleh hukum properti seperti tanah-tanah lainnya. Ia memegang peranan yang jauh lebih dalam dalam kehidupan masyarakat adat / suku. Bahkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas, warisan budaya, dan keberlanjutan kehidupan. Asal Usul dan Makna Tanah ulayat berasal dari bahasa Melayu yang berarti tanah yang diperoleh dari leluhur atau tanah turun-temurun. Dalam tradisi masyarakat adat di Indonesia, tanah ulayat tidak dimiliki oleh individu, melainkan oleh masyarakat secara kolektif. Hak kepemilikan diatur oleh aturan adat yang turun temurun diwariskan dari generasi ke generasi. Tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hukum Tanah Ulayat Hak ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, di mana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Pengakuan Tanah Ulayat Pengakuan atas hak-hak tanah ulayat menjadi penting dalam memastikan keberlanjutan masyarakat adat dan pelestarian lingkungan. Perlindungan terhadap tanah ulayat membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat adat, dan pihak terkait lainnya untuk mengembangkan kebijakan yang menghormati hak-hak tradisional dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Tanah ulayat memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat adat. Selain sebagai sumber kehidupan seperti tempat bermukim, bertani, dan berladang, tanah ulayat juga menjadi simbol keberadaan dan keberlanjutan budaya. Di dalamnya terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi fondasi kehidupan berkelompok. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Undang – undang Tanah Ulayat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”. Dengan demikian, tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan yang sebenarnya masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya dukungan masyarakat hukum adat bersangkutan atau pimpinan adat tertinggi di suatu wilayah daerah pusat. Baca Juga: Maskot Jakarta yang Hampir Punah Perlindungan dan Tantangan Meskipun memiliki nilai yang tinggi dalam kehidupan masyarakat adat, tanah ulayat seringkali menghadapi tantangan, terutama dari eksploitasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, dan konflik kepentingan dengan pihak lain. Ketidakjelasan hukum sering kali membuat tanah ulayat rentan terhadap klaim dan eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Kontribusi terhadap Pembangunan Berkelanjutan Tanah ulayat bukan hanya menjadi aset bagi masyarakat adat, tetapi juga berpotensi menjadi pilar pembangunan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, tanah ulayat dapat menjadi basis bagi pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Tetap Jaga Tanah Ulayat Tanah ulayat bukan sekadar lahan, melainkan sebuah warisan budaya dan sosial yang membentuk identitas masyarakat adat di Indonesia. Perlindungan dan pengakuan atas hak-hak tanah ulayat menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat adat. Dengan memahami nilai dan peranannya secara lebih dalam, kita dapat menghormati dan menjaga warisan budaya yang berharga bagi bangsa ini.

Sekilas Tentang Masyarakat Adat
Masyarakat adat adalah istilah umum atau konsep yang dipakai di Indonesia untuk merujuk pada komunitas-komunitas hukum adat yang sudah ada di jaman pendudukan Hindia Belanda. Dalam ilmu hukum dan teori secara formal dikenal Masyarakat Hukum Adat, tetapi dalam perkembangan terakhir, masyarakat asli Indonesia menolak dikelompokkan sedemikian mengingat perihal adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi mencakup segala aspek dan tingkatan kehidupan. Konsep Masyarakat Adat Konsep masyarakat adat telah dikembangkan oleh sarjana-sarjana hukum dan ilmu sosial sejak pada masa kolonial Belanda. Masyarakat adat sendiri adalah konsep untuk menunjuk komunitas-komunitas adat yang merupakan bagian terbesar dari populasi Hindia Belanda pada masa itu. Masyarakat adat di Indonesia membentuk bagian penting dari keragaman budaya yang kaya di negeri ini. Mereka adalah penjaga warisan nenek moyang, mewariskan tradisi, nilai-nilai, dan sistem pengetahuan yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Namun, seringkali keberadaan dan hak-hak mereka terabaikan atau bahkan terancam oleh perkembangan modernisasi dan perubahan sosial. Keberagaman Budaya Indonesia dikenal dengan keberagaman etnis, bahasa, dan budaya. Merupakan bagian integral dari kekayaan ini. Dari Sabang hingga Merauke, berbagai kelompok seperti Suku Dayak, Suku Batak, Suku Minangkabau, Suku Toraja, dan banyak lagi, hidup dengan tradisi dan budaya yang khas, mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Tradisi dan Nilai Tradisinya mencakup segala hal, mulai dari pola pemukiman, sistem pertanian, upacara adat, hingga sistem kepercayaan dan hukum adat. Nilai-nilai seperti gotong royong, kearifan lokal, dan keberlanjutan lingkungan menjadi pijakan utama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tradisi lisan, tarian, musik, dan seni rupa juga menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya mereka. Baca Juga: Apa itu Tanah Ulayat Hak-Hak dan Tantangan Masyarakat Adat Meskipun memiliki warisan budaya yang berharga, namun seringkali menghadapi tantangan besar. Hak-hak mereka atas tanah ulayat dan sumber daya alam sering diabaikan, menyebabkan konflik dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Perubahan iklim, pembangunan infrastruktur, dan modernisasi juga mengancam keberlangsungan gaya hidup tradisional mereka. Perlindungan dan Pengakuan Perlindungan yang dibutuhkan bukan hanya masalah keadilan sosial, tetapi juga kunci dalam pelestarian keragaman budaya dan keberlanjutan lingkungan. Pengakuan atas hak-hak mereka, partisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, dan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada mereka, menjadi langkah-langkah penting dalam memastikan kelangsungan hidup mereka dan keberlanjutan alam. Peran dalam Pembangunan Berkelanjutan Masyarakat adat bukanlah penghuni masa lalu, melainkan mitra penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Pengetahuan lokal mereka tentang pengelolaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati. Serta adaptasi terhadap perubahan iklim dapat menjadi aset berharga dalam menghadapi tantangan global saat ini. Masyarakat adat di Indonesia adalah bagian yang tak terpisahkan dari kekayaan budaya dan keanekaragaman yang memperkaya bangsa ini. Perlindungan, pengakuan, dan partisipasi aktif mereka dalam pembangunan berkelanjutan adalah investasi dalam masa depan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan memahami dan menghargai kontribusi mereka, kita menjaga warisan budaya yang telah ada selama berabad-abad, sambil membangun masa depan yang lebih baik bersama.

Sejarah Jamu dan Perkembangannya di Indonesia
Sejarah jamu di Indonesia tidak terlepas dari kekayaan alam negara kita yang melimpah ruah. Karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan biodiversitas terbesar di dunia, terutama tanaman / tumbuhan. Hal inilah yang menjadi salah satu sumber pemikiran orang – orang terdahulu dalam memanfaatkan hasil bumi. Selain sebagai santapan pengisi perut, tanaman – tanaman tertentu dipergunakan sebagai pengobatan suatu penyakit . Mungkin hal seperti ini bisa disebut lumrah, karena hampir semua manusia dibelahan penjuru bumi memanfaatkan hasil alam untuk kebutuhan pangan dan kesehatan mereka. Bahkan hingga saat ini masih ada suku-suku tertentu di pedalaman Indonesia yang masih menjalankan tradisi itu secara primitif, seperti suku-suku di pedalaman Papua, Kalimantan atau suku Baduy di Provinsi Banten. Jamu Dari Masa ke Masa Tetapi lain halnya dengan jamu, istilah jamu mulai ramai dipergunakan di masa – masa kerajaan jawa dahulu kala ( Beberapa kalangan ada yang mendeskripsikan Kerajaan Mataram kuno, tetapi ada juga yang mendeskripsikan Kerajaan Mataram baru ). Namun disini kita menyimpulkan bahwa jamu sudah ada sejak jaman Mataram kuno atau sekitar abad ke 7-8 masehi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa relief bergambar orang sedang menumbuk dan meminum jamu di beberapa candi yang berada di Jawa Tengah. Awalnya jamu hanya sebagai minuman khusus kalangan bangsawan di lingkungan kerajaan atau para punggawa /pasukan perang yang biasa mengkonsumsinya. Dengan kata lain jamu adalah minuman berkhasiat untuk kaum kelas atas. Peraciknya pun bukan sembarang orang atau siapa saja, tapi seseorang yang disebut Acaraki atau orang yang mempunyai kekuatan supranatural dan mahir dalam mengolah dan meramu jamu dengan pengakuan resmi dari pihak kerajaan. Manfaat Jamu Sama halnya dengan ramuan zhongyi dari China atau ginseng dari Korea, bahan jamu biasanya memanfaatkan akar-akar rimpang, dedaunan serta kulit atau batang tanaman tertentu yang memiliki khasiat untuk kesehatan. Beberapa artikel menyebut bahwa kata jamu adalah singkatan dari bahasa Jawa kuno yaitu jampi dan usada yang artinya jampi ( mantra / doa ) dan usada ( kesehatan ). Dengan kata lain jamu adalah ramuan khusus untuk kesehatan yang telah diberi mantra atau doa – doa tertentu. BACA JUGA: 8 Jenis Jamu Gendong Seiring berjalan nya waktu, jamu terus berkembang secara dinamis. Semula hanya kaum tertentu di lingkup kerajaan yang biasa mengkonsumsi jamu, perlahan mulai menyebar ke masyarakat umum. Hal ini tidak terlepas dari peran para budak-budak kerajaan zaman dulu yang biasa melihat tradisi mengolah dan mengkonsumsi jamu di dalam lingkup kerajaan kemudian dicoba dirumah masing-masing sampai menjadi tradisi yang tidak terlepaskan bagi masyarakat Jawa dahulu. Bahkan tradisi minum jamu bukan lagi untuk penyembuhan penyakit, melainkan untuk menjaga kecantikan dan perawatan tubuh para wanita dahulu. Bertahan berabad-abad lamanya, tradisi jamu tetap terpelihara dari masa ke masa. Hal itu diperkuat oleh karakteristik masyarakat Jawa dahulu yang selalu menjaga tradisi leluhurnya secara turun temurun dengan sangat apik dan penuh tanggung jawab. Jauh sebelum kaum kolonial datang ke nusantara, pengobatan segala jenis penyakit masih bertumpu pada ramuan berbahan dasar dari alam ( tanpa kimia ). Jamu di Masa Kolonial Belanda Sampai tiba kaum kolonial di nusantara tradisi jamu menjadi suatu hal yang menarik bagi beberapa kalangan kaum kolonial. Para peneliti dan dokter – dokter Belanda yang tertarik dengan jamu tak jarang belajar langsung kepada dukun / tabib yang pandai meracik ramuan untuk jamu. Bahkan sudah ada beberapa buku / jurnal yang dibuat oleh dokter – dokter Belanda yang membahas tentang praktek pengobatan dengan menggunakan ramuan jamu. Karena pada abad 16 pengobatan modern Eropa sedang berekspansi ke seluruh penjuru dunia, hal itu juga yang membuat eksistensi jamu mulai menyusut. Karena pengaruh kolonial yang sangat kuat merangsek kedalam semua lini kehidupan masyarakat, membuat tradisi masyarakat pun mulai berubah. Namun demikian tradisi jamu terus bertahan karena telah mengakar pada setiap individu masyarakat Jawa dahulu. Filosofi Jamu Secara historis jamu mempunyai nilai filosofis yang tinggi , dimana orang-orang terdahulu tidak sembarangan dalam membuat jamu. Ada beberapa jamu yang wajib / selalu diutamakan dalam pembuatannya dan sangat berkaitan erat dengan nilai – nilai kehidupan. Begitupun tahapan-tahapan dalam mengkonsumsi jamu itu sendiri. Proses Pembuatan dan aturan mengkonsumsi jamu yang populer dibagi menjadi 8 bagian. Hal ini merunut pada arah penjuru angin yang berjumlah 8. Mulai dari kunir asem, beras kencur, cabe puyang, pahitan, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup dan sinom. Kedelapan jenis jamu itu dikonsumsi sesuai urutan rasa, dimulai dari manis-asam, pedas – hangat, pedas pahit, tawar dan kembali ke manis. Urutan tersebut merupakan representasi dari perjalanan kehidupan manusia, dimana rasa manis adalah masa balita dan anak-anak. Kemudian rasa asam merupakan representasi dari kondisi remaja tanggung ketika manusia melihat samar-samar kehidupan yang sebenarnya. Berikutnya adalah masa pradewasa yang disimbolkan dengan beras kencur. Di masa ini manusia mulai memasuki tahap kedewasaan, dimana di masa-masa ini biasanya masa percobaan dan egosentris ( apapun selalu ingin dicoba tanpa memikirkan akibatnya). Rasa beras kencur yang sedikit pedas menggambarkan bahwa manusia baru merasakan sedikit saja kehidupan yang sebenarnya, atau dikenal dengan istilah ‘rang yang masih bau kencur’. Rasa cabe puyang adalah rasa pahit dan pedas yang dialami manusia dalam kehidupan yang sebenarnya. Setelah itu seiring dengan berjalannya waktu, semakin tua semua rasa itu hilang dan berubah menjadi tawar. Dan pahit pun berubah menjadi manis kembali. Begitulah nilai filosofi jamu yang masih tertanam hingga saat ini. JAMU DI MASA KINI Kini eksistensi jamu sebagai warisan tradisi semakin menggaung dan populer di masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi, banyak wirausahawan baru yang melirik jamu sebagai komoditas utama bisnis mereka. Ada yang fokus menjual bahan – bahan pembuatan jamu / empon-empon, ada juga yang mengolah jamu secara kreatif. Tak hanya di gendong lagi kini para penjual jamu bisa memasarkan produknya dengan mudah hanya melalui handphone atau melalui marketplace serta media sosial yang kini menjadi salah satu tren gaya hidup masyarakat. Kemasannya pun beraneka ragam, mulai dari menggunakan botol plastik, botol kaca atau serbuk siap seduh yang dikemas secara menarik dan kekinian. Bahkan cafe-cafe atau kedai khusus yang menyediakan jamu sekarang mulai bermunculan dimana-mana. Sama halnya seperti kopi, kini jamu mulai menjadi bagian dari gaya hidup beberapa kalangan masyarakat di Indonesia. Namun demikian, penjual jamu gendong konvensional tetap bertahan dengan profesi mereka. Bahkan boleh disebut merekalah yang menjadi ujung tombak pelestari

Orang Sunda Harus Tahu Arti & Makna Sunda?
Suku Sunda merupakan salah satu suku terbesar kedua di Indonesia yang keberadaannya saat ini telah menyebar ke berbagai pelosok Nusantara. Sebagai salah satu bagian dari suku Sunda, tentunya saya ingin berbagi informasi seputar Sunda dan Kasundaan. Dengan harapan semoga nilai tradisi adat budaya sunda yang luhur tetap terjaga dan terpelihara dari setiap generasi ke generasi berikutnya. Arti Kata Sunda Ada berbagai pandangan mengenai makna yang terkandung dalam kata Sunda tergantung pada Bahasa yang digunakan untuk menafsirkannya. Berikut ini beberapa arti kata Sunda menurut Bahasa Sunda, Sangsekerta serta dalam kajian geogolgi dan geografi: A.Bahasa Sunda SUNDA berasal dari sa-unda ->da-tunda, mengandung arti tempat menyimpan padi, lumbung SUNDA berasal dari kata sonda, artinya bagus, indah, senang atau unggul SUNDA berasal dari kata sonda, artinya puas hati, setuju atau sesuai keinginan SUNDA dalam kata sundara, artinya laki – laki yang tampan SUNDA dalam kata sundari, artinya perempuan yang cantik rupawan SUNDA artinya indah, molek B.Bahasa Sansekerta SUNDA, berakar kata sund, artinya bercahaya, terang benderang SUNDA, salah satu nama dari Dewa Wisnu yang mempunyai 1000 nam SUNDA, nama salah satu daitya, yaitu seorang satria raksasa dalam cerita Upa Sunda dan Ni Sunda dalam sastra Adiparwa pada Epois Mahabarata SUNDA, nama sebuah gunung pada masa silam yang berada di sebelah utara kota Bandung. Dikenal dengan Gunung Sundayang terlihat putih karena diselimuti abu vulkanik SUNDA, berasal dari kata saindhav-a, ihwal yang ada hubungannya dengan laut. SUNDA, berasal dari kata Su-dha artinya tempat yang bagus Dan masih banyak lagi yang lainnya C.Bahasa Kawi SUNDA berarti tersusun SUNDA berarti merangkap menyatu SUNDA berarti angka dua (2) dalam perhitungan Candrasangkala / Suryasangkala SUNDA berasal dari kata unda, artinya naik / terbang D. Dalam Kajian Geologi & Geografi Menurut R.W. Van Bemmelen (1949) bahwa: – SUNDA yaitu penamaan wilayah baratlaut dari India Timur yang dikelilingi system Gunung Sunda ( Circum Sunda Mountain System )sepanjang 7.000km, mulai dari kepulauan Filipina, Formosa sampai Lembah Brahmaputra di India. – SUNDA dalam SUNDA BESAR ( The Groote Sunda Islands ) adalah himpunan pulau – pulau besar di wilayah Indonesia, yaitu: Sumatera, Jawa, Madura dan Kalimantan – SUNDA dalam SUNDA KECIL (The Lesser/The Kleine Sunda Islands), meliputi Bali, Nusa Tenggara (NTT dan NTB) dan Timor – Dalam literatur Geologi dna peta bangsa asing, sampai saat ini dikenal dengan istilah: Sunda Plat, Sunda Trench, Sunda Strait. BACA JUGA: Sejarah Nama Jawa Barat Siapakah Urang Sunda Itu? Pertanyaan yang sangat menggelitik ini telah lama diperbincangkan orang. Penafsiarannya pun bermacam macam, sangat bergantung pada sudut pandang pemerhati. Bahkan pernah ada moment Ketika berbincang tentang pengertian sunda sering diasosiakan dengan konsep rasis, sukuisme, jinggoisme atau pemaknaan lain yang bernunasakan kedaerahan sempit. Untuk menjawab pertanyaan diatas, bisa ditelusuri melalui kajian demografi, kewilayahan, sosio kultural dan aspek genetika / keturunan serta lainnya. Seelah menyimak berbagai wilayah pemaknaan khususnya dari sudut pandang sosio-kultural penulis berkesimpulan bahwa ada 5 kategori untuk sesorang disebut sebagai Urang Sunda. Yaitu: 1.Sunda Subyektif Bila seseorang berdasarkan pertimbangan subyektifnya merasa bahwa dirinya adalah Urang Sunda, maka dia adalah Urang Sunda. Karena itu dia harus mengaktualisasikan dan mengaplikasikan Kasundaannya dalam berperilaku serta mempunyai konsep hidup yang NYUNDA. Artinya mampu memaknai dan mengaktualisasikan arti dan makna kata Sunda. 2.Sunda Obyektif Bila seseorang dianggap oleh orang lain sebagai Urang Sunda, maka orang tersebut sepantasnytta mampu mengaktualisasikan anggapan orang lain tersebut bahwa dirinya benar – benar Urang Sunda. Orang tersebut berkewajiban menunjukan Kasundaannya dengan cara berperilaku NYUNDA. 3.Sunda Genetik Yaitu seseorang yang secarfa keturunan dari orang tuanya mempunyai silsilah Urang Sunda Pituin (Orang Sunda Asli). Malah dalam kebudayaan sunda sering dirunut sampai pada generasi ketujuh diatas ego (Tujuh turunan, yaitu indung/bapa-nini/aki, bao, janggawareng, udeg-udeg, kait/gantung siwur dan selanjutnya sebagai karuhun). Pada masa sekarang dengan terjadinya pernikahan antar etnis, mungkin cukup ditandai dengan ibu bapaknya saja yang beretnis sunda. Keberadaan SUnda genetik ini adalah Sunatulloh. Simak intisari maknawi Al Qur’an Surat 49:19. Oleh karena itu seseorang yang secara genetic adalah Urang Sunda, maka berkewajiban untuk hidup dan berperilaku NYUNDA sebagai penanda jati dirinya. Tidaklah pantas seseorang berujar “ Kabeneran bae jadi Urang Sunda’. Subhanallah, Allah yang maha mempunyai rencan, tidak ada Sesuatupun yang kebetulan bagiNya. Maka orang yang terlahir sebagai Urang Sunda pun bukan sesuatu yang kebetulan. Itu adalah kehendak Allah SWT. Maha Sempurna Allah SWT. dengan segala ciptaan dan kehendaknya. 4.Sunda Sosio-Kultural Bila seseorang mempunyai ibu dan bapak atau salah satu diantaranya bukan Urang Sunda Pituin (Asli); namun dalam kehidupan kesehariannya, perilaku, adat istiadat, Bahasa, berkesenian, berkebudayaan, berpikir serta memopunyai konsep hidup seperti Urang Sunda. Terkadang kelompok Sunda Sosio Kultural jauh lebih Nyunda dalam berperilaku kesehariannya. Hingga saat ini sudah cukup banyak Urang SUnda dari kelompok Sunda Sosio-Kultural ini yang mengangkat nama baik dan derajat Kasundaan di tataran lokal, nasional maupun internasional. 5.Sunda Geografis-Demografis Pengelompokan ini berdasarkan administrasi kewilayahan, yaitu penghuni asli (Sunda pituin) yang secara geografis berada di tatar Sunda (Jawa Barat). Siapapun akan berbendapat bahwa Urang Sunda itu berdiam di wilayah jawa bagian barat. Ddemikian pula pengertian Tatar Sunda bisa mencakup wilayah yang lebih luas lagi termasuk kedalamnya wilayah Banten, Jawa Tengah bagian Barat, malah menurut kajian geografis menjangkau Kepulauan Sunda Besar dan Sunda Kecil. Bila demikian memaknainya, maka menjadi kewajiban kita secara geografis – demografis berada di tatar Sunda untuk selalu menjaga keberadaan dan kesejehteraan Tatar Sunda dengan seluruh cacahjiwanya. (Dikutip dari buku KASUNDAAN Rawayan Jati Karya H.R Hidayat Suryalaga)

Budaya Pamali dalam Kehidupan Masyarakat Sunda
Budaya pamali adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat Sunda yang kaya dengan tradisi dan kearifan lokal. Pamali, dalam konteks budaya Sunda, merujuk pada pantangan atau larangan yang tidak boleh dilanggar karena memiliki makna atau nilai-nilai tertentu. Konsep pamali dalam masyarakat Sunda tidak hanya mencakup tata krama dan etika sosial, tetapi juga berhubungan dengan keyakinan spiritual dan budaya lokal yang mendalam. Artikel ini akan membahas berbagai aspek pamali dalam kehidupan masyarakat Sunda, mulai dari makna, bentuk, hingga dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. 1. Makna dan Asal Usul Pamali Pamali adalah istilah dalam bahasa Sunda yang berasal dari kata “pamalik” atau “pamalikeun,” yang secara harfiah berarti “pengembalian” atau “balasan.” Konsep ini berakar dari kepercayaan bahwa setiap tindakan yang dilakukan akan mendapatkan balasan atau akibat, baik positif maupun negatif. Dalam masyarakat Sunda, pamali sering kali berkaitan dengan norma-norma sosial, adat istiadat, dan kepercayaan mistis yang sudah ada sejak zaman dahulu. Pamali tidak hanya dianggap sebagai larangan, tetapi juga sebagai bentuk pengaturan diri dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Larangan ini dianggap penting untuk menghindari dampak negatif yang mungkin terjadi jika melanggar pantangan tersebut. Dalam banyak kasus, pamali juga dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan kekuatan gaib yang dipercaya menjaga keseimbangan dunia. 2. Jenis-Jenis Pamali dalam Masyarakat Sunda Pamali dalam masyarakat Sunda dapat dibagi menjadi beberapa kategori, masing-masing dengan konteks dan aturan yang berbeda: a. Pamali Sosial Pamali sosial berkaitan dengan norma dan tata krama yang mengatur interaksi antarindividu dalam masyarakat. Beberapa contoh pamali sosial termasuk: Pamali dalam Berbicara: Misalnya, berbicara kasar atau tidak sopan kepada orang yang lebih tua dianggap pamali karena dianggap tidak menghormati hierarki sosial dan nilai-nilai sopan santun. Pamali dalam Kegiatan Sehari-Hari: Melakukan aktivitas tertentu pada waktu-waktu tertentu, seperti membunyikan suara keras pada malam hari, dianggap pamali karena dianggap dapat mengganggu ketenangan dan keharmonisan lingkungan. b. Pamali Adat Pamali adat berhubungan dengan aturan dan larangan yang berkaitan dengan adat istiadat dan upacara tradisional. Misalnya: Pamali dalam Upacara Adat: Dalam pelaksanaan upacara adat seperti pernikahan atau khitanan, terdapat pantangan tertentu yang harus dihindari untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan acara. Pamali dalam Kehidupan Sehari-Hari: Beberapa aktivitas sehari-hari mungkin dianggap pamali jika bertentangan dengan adat istiadat, seperti membangun rumah di lokasi yang dianggap tidak sesuai dengan kepercayaan adat. c. Pamali Spiritual Pamali spiritual terkait dengan kepercayaan akan kekuatan gaib dan dunia mistis. Contoh pamali spiritual meliputi: Pamali dalam Memilih Lokasi: Misalnya, membangun rumah atau tempat usaha di lokasi yang dianggap angker atau penuh dengan energi negatif dapat dianggap pamali karena dikhawatirkan akan mendatangkan sial. Pamali dalam Berinteraksi dengan Dunia Gaib: Menghindari melakukan aktivitas yang dianggap dapat mengganggu atau menyinggung makhluk halus atau roh leluhur. Baca Juga: Keunikan Masyarakat Baduy di sebelah barat Pulau Jawa 3. Dampak Pamali dalam Kehidupan Sehari-Hari Pamali memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Sunda. Beberapa dampak tersebut antara lain: a. Menjaga Keharmonisan Sosial Pamali membantu menjaga keharmonisan sosial dengan memastikan bahwa setiap individu mematuhi norma-norma yang telah disepakati. Hal ini menciptakan lingkungan yang tertib dan saling menghormati, yang pada gilirannya memperkuat ikatan sosial dalam komunitas. b. Pelestarian Adat dan Tradisi Dengan mengikuti pamali, masyarakat Sunda turut melestarikan adat istiadat dan tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur. Ini penting untuk mempertahankan identitas budaya dan memberikan rasa keterhubungan antara generasi. c. Pengendalian Diri dan Etika Pamali juga berfungsi sebagai alat pengendalian diri dan pengembangan etika pribadi. Dengan menghindari tindakan yang dianggap pamali, individu belajar untuk menghormati norma dan aturan yang ada, serta menghindari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. 4. Pamali dalam Konteks Modern Dalam konteks masyarakat modern, pamali mungkin menghadapi tantangan seiring dengan perubahan zaman dan globalisasi. Beberapa pantangan mungkin dianggap kuno atau tidak relevan oleh generasi muda yang lebih terpengaruh oleh budaya global. Namun, banyak masyarakat Sunda tetap memegang teguh nilai-nilai pamali sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Beberapa upaya dilakukan untuk menjaga relevansi pamali dalam kehidupan modern, seperti melalui pendidikan dan penyuluhan mengenai pentingnya tradisi dan adat istiadat. Organisasi budaya dan komunitas lokal sering kali terlibat dalam mengajarkan dan meneruskan nilai-nilai pamali kepada generasi berikutnya. Pamali yang tetap Eksis hingga Kini Budaya pamali merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Sunda yang berfungsi untuk menjaga keharmonisan sosial, melestarikan adat dan tradisi, serta mengendalikan perilaku individu. Meskipun pamali sering dianggap sebagai larangan yang bersifat mistis atau ketinggalan zaman, ia tetap memiliki nilai penting dalam konteks sosial dan budaya. Dengan memahami dan menghargai pamali, masyarakat Sunda tidak hanya menjaga warisan budaya mereka, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan identitas mereka dalam menghadapi perubahan zaman.

8 Jenis Jamu Gendong Yang Paling Populer
Filosofi Jamu Gendong Ada berbagai macam jenis jamu tradisional yang terkenal di seluruh Nusantara. Namun yang paling populer adalah 8 Jenis Jamu Yang Dijual Mbok Jamu Gendong. Sesuai dengan nilai Filosofi Jamu yang masih tetap dipegang teguh para penjual Jamu Gendong sampai saat ini, bahwa 8 jenis tersebut sesuai dengan arah mata angin dan fase perubahan / perkembangan kehidupan manusia. Sudah sejak dahulu kala jamu dijadikan salah satu cara pencegahan dan pengobatan suatu penyakit. Karena manfaatnya yang luar biasa bagi tubuh. Bahan dasar pembuatan jamu tradisional berasal dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan berbagai jenis bahan alami lainnya. Kini varian jenis jamu semakin berkembang dan inovatif. Mulai dari rasa, bahan, cara penyajian sampai metode penjualannya yang mengikuti perkembangan jaman. Yuk ketahui 8 jenis jamu tradisional yang dijual Mbok Jamu Gendong berikut ini : 1. Kunyit Asam Jamu kunyit asam adalah salah satu jenis jamu yang wajib disajikan oleh penjual jamu gendong. Jamu ini dibuat dari bahan utama buah asam dan rimpang kunyit. Jamu ini sangat mudah dikenali, karena memilik warna kuning cenderung oranye yang berasal dari senyawa kurkumin. Selain rasanya yang segar kunyit asam memiliki fungsi sebagai antioksidan yang baik bagi tubuh, anti-inflamasi, serta anti kanker. Biasanya, para wanita mengonsumsi kunyit asam ini ketika sedang haid. Kunyit asam tersebut dipercaya dapat mengatasi nyeri ketika sedang haid, karena mengandung senyawa curcumenol yang berfungsi sebagai analgetik. 2. Beras Kencur Jamu Beras kencur dibuat dari bahan baku beras dan diberi campuran rimpang kencur. Kandungan kencur tersebut dipercaya memiliki fungsi antioksidan yang efektif menjaga tubuh dari zat berbahaya. Manfaat jamu beras kencur ini dipercaya mampu mengontrol berat badan tubuh dan juga membantu mengatasi diabetes jika dikonsumsi secara rutin. 3. Temulawak Jenis Jamu Tradisonal berikutnya adalah temulawak. Jamu yang terbuat dari temulawak dan asam jawa serta daun pandan dan jinten ini dipercaya dapat mengobati mual, kembung, dan masuk angin. Jamu temulawak mengandung Antioksidan yang sangat berguna untuk mencegah terjadinya kerusakan sel pada mukosa lambung yang diakibatkan radikal bebas. BACA JUGA: 5 Pantai di Bali Terbaik 4. Galian Singset Jamu galian singset ini terbuat dari kencur, temulawak, kapulaga, daun jati belanda, asam jawa, kunyit, merica, laos, biji pinang, kayu manis, serai, cengkeh, ketumbar, dan berbagai rempah lainnya. Biasanya, jamu ini digunakan sebagai jamu untuk menjaga bobot badan ideal. Jamu ini memang memiliki kandungan antiobesitas dan antidislipidemia, yang terdapat pada bahan campurannya, seperti daun jati belanda, kunyit, dan biji pinang. 5. Sinom Jamu tradisional sinom hampir mirip dengan jamu kunyit asam namun diberi tambahan gula merah, temulawak dan rempah – rempah lainnya. Jamu Sinom mengandung senyawa yang bermanfaat dan dipercaya dapat meremajakan kulit, mencerahkan kulit, serta meredakan nyeri haid. 6. Kudu Laos Jamu tradisional ini terbuat dari mengkudu dan laos atau lengkuas. Manfaat dari kudu laos ini sangat banyak sekali diantaranya untuk meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah diabetes, mencegah kanker, memulihkan sel, serta menjaga kesehatan kulit, mencegah kanker, meredakan batuk, merawat kulit, hingga meningkatkan kesuburan pada pria dewasa. 7. Kunci Sirih Jamu yang terbuat dari temu kunci dan suruh atau sirih ini dipercaya memiliki khasiat untuk mengobati keputihan dan anti diabetes. Jamu kunci sirih cocok dikonsumsi secara rutin oleh kaum wanita dewasa. Agar dapat membantu masalah seputar kewanitaan. 8. Pahitan Jamu pahitan ini dibuat dari daun sambiloto yang sangat pahit namun kaya manfaat plus brotowali yang tak kalah pahit rasanya. Meskipun begitu, jamu pahitan ini dipercaya memiliki berbagai manfaat dalam menyembuhkan berbagai penyakit, seperti menjaga kesehatan perut dan pencernaan, menambah nafsu makan, mengatasi bau badan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan bahkan jamu tradisional ini juga dipercaya dapat mencegah jerawat. Itulah 8 jenis jamu tradisional yang dijual Mbok Jamu Gendong yang biasanya berkeliling menyambangi rumah setiap harinya. Apabila dikonsumsi secara rutin khasiat dari jamu diatas akan sangat terasa dan bermanfaat sekali bagi tubuh. Untuk itu mari kita biasakan mengkonsumsi jamu setiap hari agar warisan nenek moyang sejak dulu kala ini tetap lestari dan berkembang. (dwd)